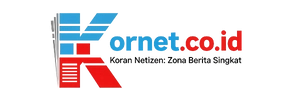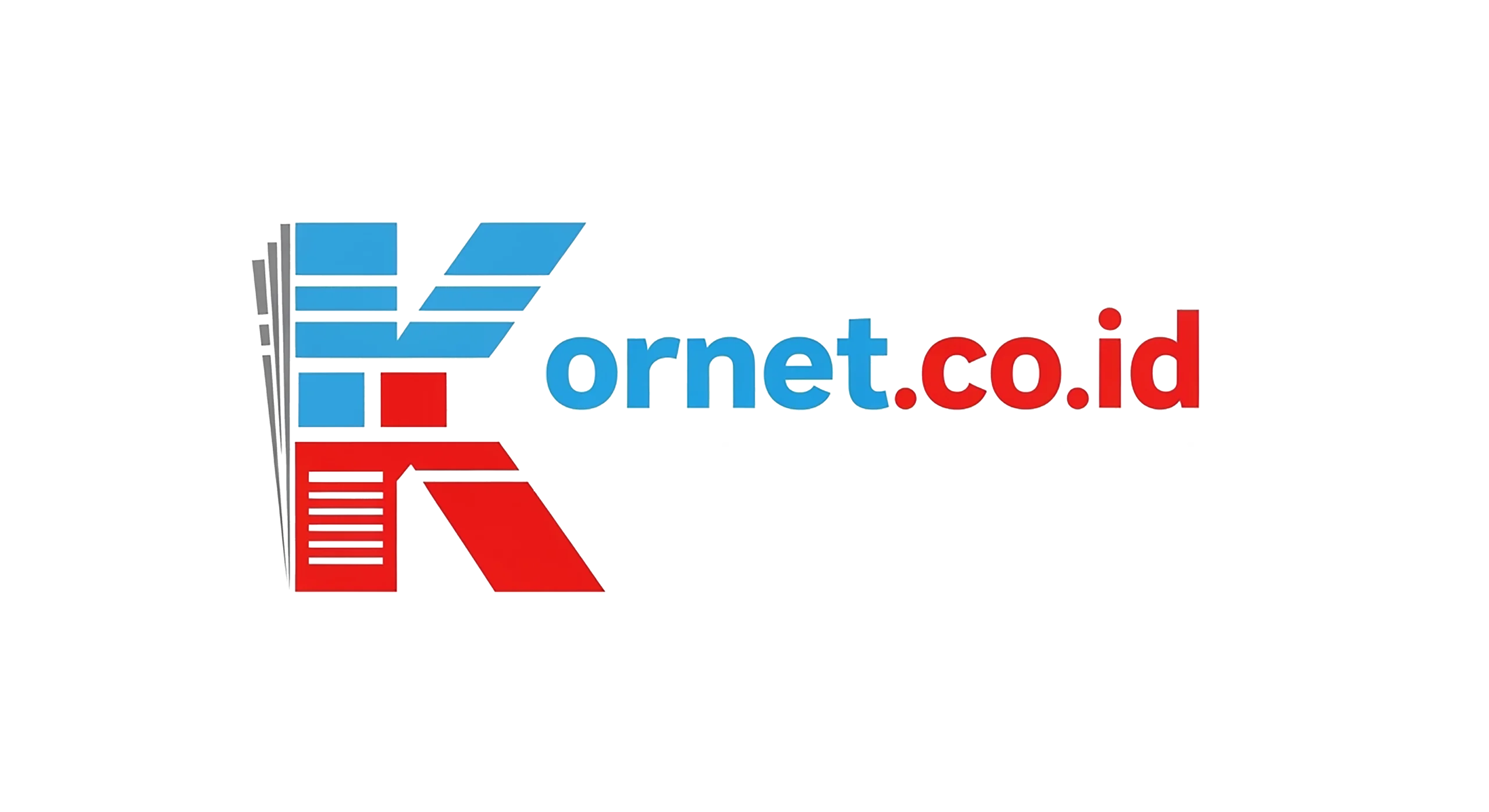Fenomena Viral yang Mengundang Tawa dan Renungan
kornet.co.id – Jagat media sosial kembali diramaikan oleh sebuah video yang menampilkan sekelompok emak-emak di Lumajang dengan permintaan yang terdengar tak lazim: Gunung Semeru diminta untuk dipindahkan. Pernyataan itu sontak memantik gelombang reaksi publik. Ada yang tertawa, ada yang mengernyitkan dahi, dan tak sedikit pula yang mengajak berpikir lebih dalam. Di balik viralitasnya, peristiwa ini menyimpan lapisan makna yang lebih kompleks daripada sekadar humor spontan.
Permintaan tersebut muncul di tengah kekhawatiran warga terhadap aktivitas vulkanik dan dampak bencana yang kerap menghantui kawasan sekitar. Dalam bahasa yang polos, lugas, dan emosional, para emak-emak itu menyuarakan keresahan kolektif. Kalimatnya sederhana. Namun resonansinya luas.
Gunung Semeru: Antara Sakralitas dan Ancaman
Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru bukan sekadar bentang alam. Ia adalah simbol. Ia adalah poros kosmologis. Dalam banyak narasi budaya, Semeru dipandang sakral, tempat bersemayamnya nilai spiritual dan keseimbangan alam. Namun bagi warga yang hidup di kaki gunung, realitasnya sering kali ambivalen.
Letusan, awan panas, dan lahar dingin bukan konsep abstrak. Ia nyata. Ia menghancurkan ladang, rumah, dan rasa aman. Ketika ancaman berulang hadir, rasa lelah pun menumpuk. Dalam kondisi inilah, logika rasional kerap berkelindan dengan ekspresi emosional. Permintaan memindahkan Gunung Semeru lahir dari ketidakberdayaan yang diartikulasikan secara ekstrem.
Bahasa Emosi dalam Ruang Digital
Media sosial memiliki kecenderungan menyederhanakan pesan. Ia mengamplifikasi yang unik, yang janggal, yang mengundang tawa. Video emak-emak Lumajang itu pun mengalami nasib serupa. Dipotong. Diberi judul sensasional. Didorong algoritma. Viralitas tercipta.
Namun di balik sorotan kamera dan komentar warganet, terdapat bahasa emosi yang sering luput dibaca. Emosi kolektif masyarakat terdampak bencana kerap menemukan jalannya melalui ungkapan-ungkapan non-teknis. Mereka tidak berbicara dalam terminologi mitigasi. Mereka berbicara dalam bahasa rasa.
Rasionalitas Publik dan Humor Sosial
Sebagian publik menanggapi peristiwa ini dengan humor. Meme bermunculan. Sindiran halus dilontarkan. Dalam konteks budaya digital, tawa sering menjadi mekanisme pertahanan. Ia meredakan ketegangan. Ia menjembatani absurditas.
Namun humor sosial juga memiliki sisi reflektif. Ia membuka ruang diskusi tentang literasi kebencanaan. Tentang bagaimana informasi ilmiah disampaikan. Tentang jarak antara kebijakan dan pengalaman warga. Ketika emak-emak meminta Gunung Semeru dipindah, yang sebenarnya mereka minta mungkin adalah rasa aman yang lebih nyata.
Mitigasi Bencana dan Kesenjangan Komunikasi
Indonesia berada di cincin api. Risiko bencana adalah keniscayaan. Namun mitigasi bukan hanya soal peta rawan dan sirene peringatan. Ia juga tentang komunikasi yang empatik. Tentang kehadiran negara yang terasa.
Kesenjangan komunikasi sering membuat masyarakat merasa ditinggalkan. Informasi teknis tidak selalu menjawab kecemasan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, permintaan irasional bisa muncul sebagai bentuk protes simbolik. Gunung Semeru menjadi metafora dari masalah yang lebih besar: ketidakpastian hidup di bawah bayang-bayang bencana.
Perempuan, Komunitas, dan Suara Akar Rumput
Menariknya, suara yang viral kali ini datang dari emak-emak. Dalam banyak komunitas, perempuan adalah penjaga stabilitas rumah tangga. Mereka merasakan langsung dampak bencana terhadap air, pangan, dan anak-anak. Ketika mereka bersuara, yang dibawa bukan sekadar opini, melainkan pengalaman hidup.
Permintaan memindahkan Gunung Semeru bisa dibaca sebagai ekspresi kelelahan struktural. Kelelahan menghadapi relokasi sementara. Kelelahan menghadapi janji bantuan. Kelelahan menghadapi ketidakpastian yang berulang.
Antara Realitas Ilmiah dan Realitas Sosial
Secara ilmiah, memindahkan gunung adalah kemustahilan. Alam memiliki hukum sendiri. Namun realitas sosial tidak selalu tunduk pada logika ilmiah. Ia tunduk pada rasa aman, pada persepsi, pada trauma kolektif.
Di sinilah pentingnya jembatan antara sains dan masyarakat. Edukasi kebencanaan harus membumi. Bahasa harus disesuaikan. Pendekatan harus manusiawi. Gunung Semeru tidak bisa dipindah, tetapi risiko dan dampaknya bisa dikelola dengan lebih adil dan inklusif.
Refleksi di Balik Viralitas
Viralitas adalah pedang bermata dua. Ia bisa mereduksi persoalan menjadi lelucon. Ia juga bisa membuka mata publik. Peristiwa emak-emak Lumajang ini seharusnya dibaca sebagai sinyal. Bahwa ada kegelisahan yang belum sepenuhnya terjawab.
Alih-alih sekadar menertawakan, publik perlu mendengar. Pemerintah perlu hadir. Media perlu mengelaborasi. Karena di balik permintaan memindahkan Gunung Semeru, tersimpan harapan sederhana: hidup yang lebih aman, lebih tenang, dan lebih pasti.
Dan harapan itu, meski diucapkan dengan cara yang terdengar mustahil, adalah sesuatu yang sepenuhnya manusiawi.