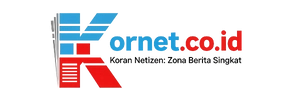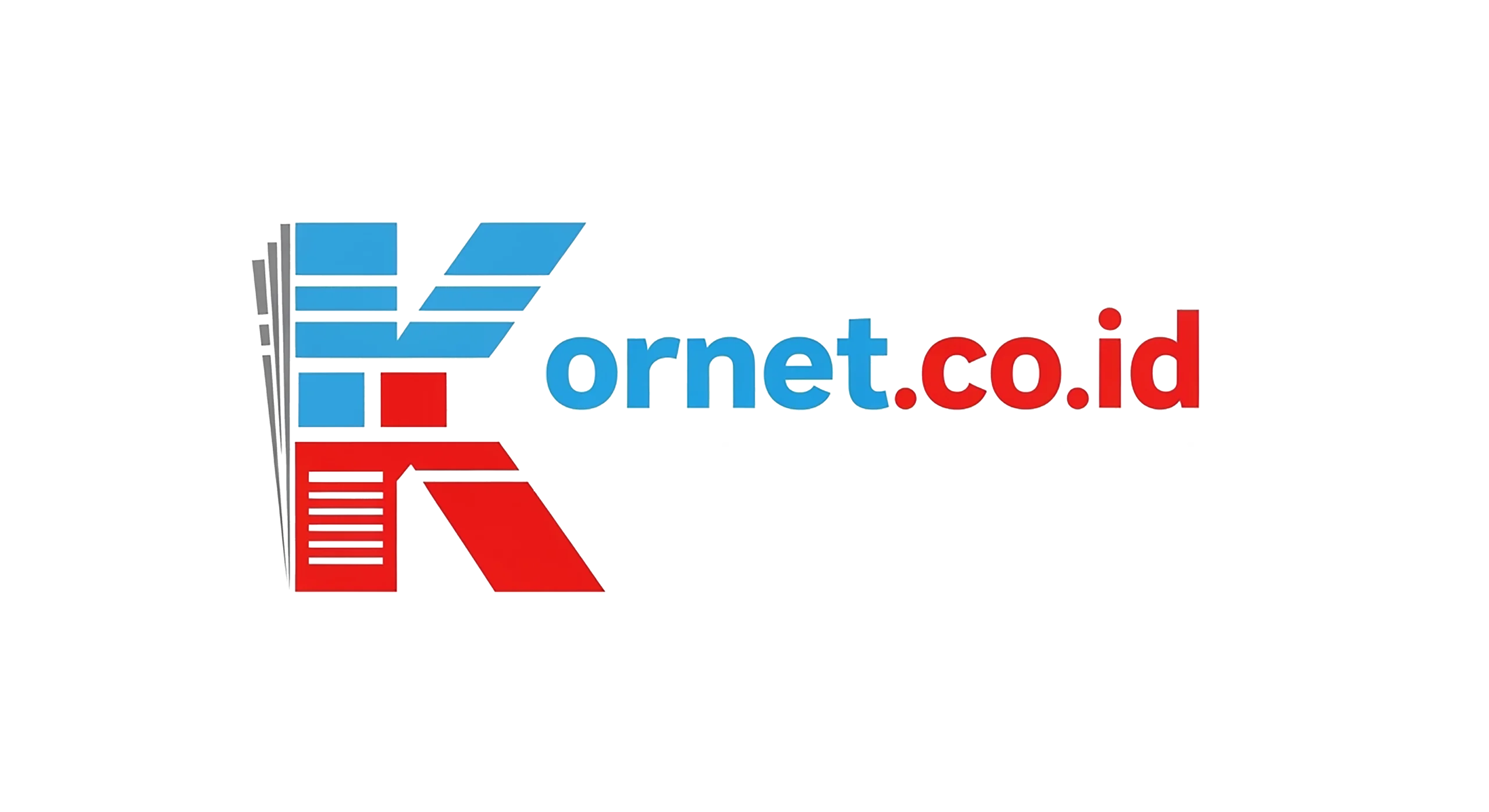kornet.co.id – Dalam setiap keluarga, hubungan antara menantu dan mertua kerap kali menjadi dinamika yang kompleks. Ada yang penuh kasih, hangat, dan saling mendukung. Namun, tak sedikit pula yang justru menjadi ladang konflik dan ketegangan. Beberapa kasus bahkan menyingkap sisi gelap dari relasi ini — seperti kisah yang baru-baru ini viral dan mengguncang hati banyak orang.
Seorang perempuan muda tengah berjuang antara hidup dan mati di ruang persalinan. Di saat yang seharusnya penuh doa dan dukungan, ia justru menerima kalimat paling menyakitkan dari orang yang seharusnya menjadi figur ibu kedua dalam hidupnya. Sang mertua, tanpa empati sedikit pun, melontarkan ucapan: “Biar mati juga, tapi lahirkan dulu itu anak.”
Kalimat tersebut tidak hanya menyayat hati, tapi juga membuka kembali luka-luka emosional yang dialami oleh banyak perempuan lainnya yang hidup dalam relasi keluarga toksik.
Ketika Kata Lebih Tajam dari Luka

Kalimat kasar yang dilontarkan oleh seorang mertua kepada menantunya itu menjadi viral karena menyentuh sisi kemanusiaan yang sangat dalam. Dalam budaya Indonesia yang kental dengan nilai kekeluargaan dan gotong royong, kejadian ini terasa seperti tamparan keras. Betapa sebuah hubungan yang seharusnya dipenuhi pengertian dan empati, justru menjadi sarang ketegangan dan tekanan emosional.
Apa yang dikatakan sang mertua bukanlah sekadar kata-kata. Itu adalah bentuk nyata dari dehumanisasi — menjadikan seorang menantu tak lebih dari alat untuk melahirkan keturunan. Seakan-akan nyawa sang perempuan bisa ditukar demi hadirnya bayi, tanpa memedulikan keselamatannya sebagai individu yang juga punya nilai dan hak hidup.
Menantu: Posisi Rentan dalam Sistem Patriarki
Di banyak keluarga Indonesia, menantu — terutama perempuan — kerap kali menempati posisi yang rentan. Ia masuk ke dalam keluarga yang sudah memiliki sistem, budaya, dan hierarki yang berjalan lama. Tidak sedikit menantu yang dipaksa menyesuaikan diri tanpa diberi ruang untuk bersuara. Ketika hubungan dengan mertua tidak harmonis, yang terjadi adalah penindasan emosional secara terus-menerus.
Relasi ini menjadi lebih rumit ketika peran mertua terlalu dominan dalam rumah tangga anaknya. Alih-alih menjadi penasihat yang bijaksana, beberapa mertua justru mengambil alih kendali, bahkan dalam keputusan-keputusan pribadi seperti pengasuhan anak, keuangan, hingga urusan medis.
Tekanan Sosial & Budaya: Membentuk Mertua yang ‘Berkuasa’
Di lansir dari jabar.tribunnew Tidak bisa dipungkiri, sistem patriarki dan nilai-nilai tradisional turut menyumbang terhadap terbentuknya sikap otoriter sebagian mertua terhadap menantu. Budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemilik rumah tangga dan perempuan sebagai “pendatang” yang harus tunduk, membuat sang menantu kerap kehilangan otonomi atas tubuh dan kehidupannya.
Dalam konteks ini, mertua sering merasa berhak menentukan apa yang terbaik — bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk menantunya. Kehamilan, persalinan, hingga pola asuh anak pun dianggap sebagai urusan yang dapat mereka kontrol. Maka ketika menantu dianggap lemah, membangkang, atau tidak sesuai ekspektasi, tak jarang ia dijadikan sasaran tekanan verbal, bahkan emosional.
Trauma yang Tak Terlihat

Apa yang dialami sang menantu dalam kisah ini tidak hanya luka fisik. Kata-kata tajam dari mertua bisa membekas jauh lebih dalam daripada luka jahitan persalinan. Trauma psikologis yang ditimbulkan bisa berujung pada depresi pasca-melahirkan, gangguan kecemasan, bahkan perasaan tidak berharga sebagai perempuan dan ibu.
Lebih menyedihkan lagi, banyak korban dalam situasi serupa memilih diam. Mereka takut dianggap durhaka jika mengeluh tentang perlakuan mertua. Mereka enggan bercerita karena khawatir dianggap memperkeruh hubungan keluarga. Akhirnya, mereka menanggung luka dalam diam — dan menyimpannya dalam ruang-ruang sunyi yang tak terjamah.
BACA JUGA : Trump Kirim Kapal Selam Nuklir ke Perbatasan Rusia, Tanggapi Provokasi Medvedev
Saatnya Mengubah Paradigma
Kisah menyakitkan ini seharusnya menjadi momen refleksi kolektif. Hubungan mertua dan menantu harus dibangun atas dasar rasa hormat dua arah. Tidak ada satu pihak yang lebih tinggi atau lebih berhak dari yang lain. Setiap orang, termasuk menantu, berhak atas perlindungan, penghargaan, dan cinta dalam keluarga.
Kita perlu membongkar konstruksi sosial yang masih menempatkan menantu perempuan sebagai pihak yang “berhutang budi” dan “harus menyesuaikan diri sepenuhnya.” Hubungan keluarga tidak seharusnya berjalan satu arah. Ketika seorang perempuan telah menjadi istri dan ibu, maka dia berhak memiliki suara — bahkan dalam keputusan yang menyangkut hidup dan mati.
Peran Suami sebagai Penengah
Dalam dinamika seperti ini, suami memegang peranan vital. Ia tidak boleh menjadi sosok pasif yang hanya menyaksikan. Suami harus menjadi jembatan yang adil, membela ketika istri diperlakukan tidak adil, dan menjaga agar mertua tidak melampaui batas. Keberpihakan suami pada keadilan adalah kunci untuk menciptakan keluarga yang sehat.
Namun sayangnya, banyak suami justru memilih diam atau berpihak pada orang tua demi menghindari konflik. Padahal, keberanian untuk bersikap adil adalah bentuk tanggung jawab moral yang tak bisa ditawar.
Tindakan Hukum dan Perlindungan Psikologis
Jika terjadi kekerasan verbal atau emosional secara terus-menerus dari mertua kepada menantu, bukan hal yang berlebihan untuk mempertimbangkan pendampingan psikologis, bahkan konsultasi hukum. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Indonesia juga mencakup kekerasan verbal dan psikologis sebagai bentuk kekerasan domestik.
Keluarga besar, tokoh masyarakat, dan lembaga pendamping perempuan perlu turun tangan dalam membangun kesadaran bahwa kekerasan tidak selalu harus berupa fisik. Kata-kata yang menjatuhkan, mengancam, atau melecehkan, juga sama berbahayanya.
Penutup: Saatnya Membangun Ulang Arsitektur Keluarga
Membangun keluarga bukan hanya tentang menyatukan dua individu, tapi juga dua budaya, dua pola pikir, dan dua sejarah kehidupan. Relasi antara menantu dan mertua tidak bisa dipaksakan untuk langsung harmonis. Ia butuh proses, pemahaman, dan komitmen untuk saling menghargai.
Kalimat seperti “biar mati juga, tapi lahirkan dulu itu anak” tidak boleh lagi terjadi di tengah masyarakat yang mengaku menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Tidak ada satu pun nyawa yang pantas dianggap remeh. Karena di balik setiap kelahiran, ada perjuangan hidup yang tidak bisa digantikan oleh siapa pun.
Sudah saatnya keluarga menjadi ruang yang menyembuhkan, bukan yang melukai. Sebab cinta yang sebenarnya, bukan tentang menguasai — tapi merawat, menerima, dan menghargai.