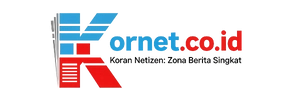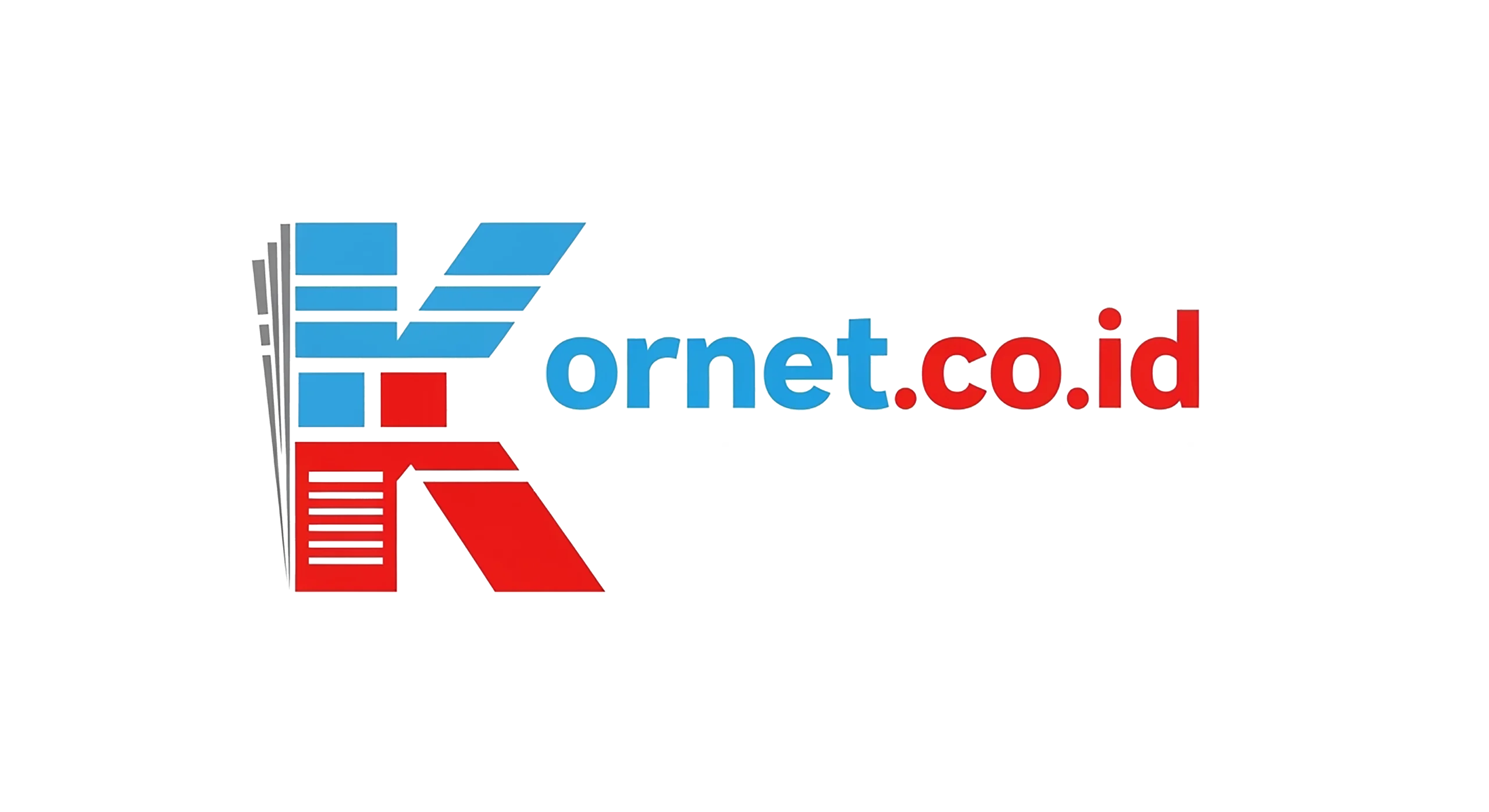Kornet.co.id – Kasus yang terjadi di Jambi beberapa waktu belakangan memantik turbulensi opini publik. Kabar tentang seorang dosen yang terseret persoalan hukum, lalu kemudian nama seorang anggota polisi muda turut masuk dalam pusaran pemberitaan, membuat jagat percakapan digital mendidih. Narasi ini viral dalam hitungan jam. Media sosial terisi oleh perdebatan, gosip, kontra-gosip, potongan narasi yang saling melompat.
Fakta bahwa salah satu figur yang ikut disebut dalam arus pemberitaan itu adalah Bripda Waldi, membuat situasinya tambah bising, karena publik selalu memberi perhatian lebih ketika ada rangkaian isu yang menyangkut aparatur negara. Inilah salah satu dinamika paling terlihat: publik jauh lebih cepat mengonsumsi narasi daripada memverifikasi narasi.
Pola konsumsi informasi publik digital kita memang seperti itu hari ini. Kecenderungan untuk menyederhanakan konteks menjadi drama linear. Padahal sebuah kasus hukum — terlebih ketika masih berjalan — tidak pernah linear. Ia kompleks, berlapis, dan berisi proses verifikasi yang panjang.
Mengapa kasus ini bisa menggegerkan?
Ada elemen-elemen tertentu yang menjadikan kasus Jambi ini mencuat dan mengkontaminasi kesadaran publik nasional. Pertama, ada unsur akademisi. Dosen selalu diasosiasikan dengan “kesucian intelektual”, dengan pengetahuan, dengan kredibilitas. Ketika seorang dosen terseret persoalan hukum, publik merasakan “kebocoran kepercayaan” pada sistem pembelajaran tinggi.
Kedua, ada figur aparatur kepolisian yang disebut-sebut bernama Bripda Waldi. Kapasitas polisi identik dengan aparat penegak hukum. Sehingga publik segera memosisikan diri dalam mode “audit moral”: seolah semua orang menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi panel etik dalam komentarnya masing-masing.
Ketiga, seluruh dinamika terjadi dalam ekosistem media sosial yang hyperconnected. Di Jambi, isu lokal bisa menjadi isu nasional dalam waktu kurang dari 24 jam.
Keempat, narasi ini memadukan 2 entitas institusional: kampus dan kepolisian. Ini dua institusi yang di dalam imajinasi publik idealnya steril dari drama. Ketika keduanya tercantel dalam satu pemberitaan, efek psikologisnya jauh lebih keras.
Kerentanan Etika Profesional di Era Teknologi
Dilansir dari Detik.com Kasus ini, tanpa perlu menuding siapapun, mengajari sebuah pelajaran besar: kompetensi profesional bukan sekadar kemampuan teknis. Ada elemen etika, integritas, dan akuntabilitas yang harus paralel. Kompetensi tanpa etika hanya akan menjadi pisau bermata dua.
Apalagi di era pasca 2020 — era ketika digitalisasi merasuk ke semua sektor, termasuk pendidikan tinggi dan penegakan hukum. Teknologi mempercepat kinerja, mempercepat alur kerja, tetapi juga mempercepat potensi penyimpangan ketika pengawasan etik tidak memadai.
Figur seperti Bripda Waldi disorot bukan hanya karena statusnya, tetapi karena perspektif publik tentang “keahlian internal”: jika seseorang punya keahlian teknis tertentu — maka publik menduga ia bisa melakukan banyak hal. Dugaan publik itu bisa liar. Dan ketika publik sudah mengolah sendiri “kemungkinan”, narasi bisa melenceng jauh meninggalkan fakta.
Viral bukan valid
Inilah mantra penting yang harus kembali diulang dalam konteks public discourse hari ini. Viral ≠ valid.
Kasus Jambi ini menjadi contoh nyata bahwa persepsi kolektif bisa berubah drastis hanya dalam satu-dua unggahan anonim, yang kemudian diteruskan berkali-kali, lalu membentuk citra baru yang diterima seolah itu adalah realitas utuh.
Padahal proses verifikasi hukum adalah proses prosedural, berlapis, dan tidak boleh diintervensi oleh “trial by social media”. Negara punya konstitusi. Ada due process. Ada hak setiap individu untuk mendapatkan pembuktian dan pembelaan yang proporsional.
Mengapa isu ini harus dibaca serius secara sosial?
Sebab ada konsekuensi sosial-psikologis yang bisa bertahan lama dibanding umur viralitasnya. Publik bisa menjadi semakin sinis terhadap kampus. Publik bisa menjadi semakin cemas terhadap institusi keamanan. Publik bisa kehilangan kepercayaan pada legal due process.
Padahal institusi tidak identik dengan individu.
Ketika satu kasus terjadi, itu bukan berarti seluruh tubuh institusi ikut cacat. Publik perlu membedakan: ada personal accountability dan ada institutional accountability. Dua hal ini tidak bisa digabung seenaknya dalam opini digital yang emosional.
Negara dan lembaga tinggi harus membangun protokol komunikasi krisis
Ini bukan era 1990-an, ketika krisis hanya bermain di halaman 1 koran. Sekarang krisis reputasi berjalan di kecepatan real-time. Negara, aparat, dan kampus harus berpikir ulang tentang model komunikasi publik.
Harus dibangun protokol komprehensif saat menghadapi krisis:
- siapa berbicara
- data apa yang boleh dipublikasi
- apa batas etika komunikasi publik
- bagaimana menjelaskan kompleksitas tanpa membuka detail sensitif
Tanpa protokol yang baik — maka setiap kasus akan berubah menjadi drama kolektif. Dan setiap drama kolektif akan meninggalkan residu perpecahan sosial.
Penutup
Kasus dosen di Jambi yang menghebohkan — dan penangkapan aparat muda seperti Bripda Waldi yang ikut mencuat di dalam arus narasi — adalah alarm keras bagi ekosistem sosial kita. Bukan semata-mata karena skandalnya. Tetapi karena apa yang ia wariskan: pelajaran tentang betapa rapuhnya konstruksi makna di era digital.
Kita sebagai publik harus belajar memperlambat diri.
Belajar menunggu fakta lengkap.
Belajar memisahkan emosi dari analisis.